Oleh: Gusai Fabanyo
Komite Pimpinan Pusat Samurai Maluku Utara
_______
HALMAHERA, pulau terbesar di provinsi Maluku Utara, kini tidak lagi menjadi rumah yang tenang bagi masyarakatnya. Di balik lanskap alam yang mempesona, hutan yang dulu lebat, dan laut yang kaya akan biota, kini berdiri pabrik-pabrik pengolahan nikel dan kawasan industri tambang yang terus meluas. Pertanyaannya: itu semua sebenarnya untuk siapa?
Dalam beberapa tahun terakhir, investasi besar-besaran di sektor pertambangan dan industri nikel, terutama di kawasan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, telah merombak wajah pulau ini. Atas nama pembangunan dan percepatan ekonomi nasional, ruang hidup masyarakat adat dan ekosistem lokal telah dikorbankan. Sungai-sungai tercemar, tanah kehilangan kesuburannya, dan konflik agraria tak bisa terhindarkan. Ironisnya, masyarakat yang telah turun-temurun tinggal dan menjaga tanah ini justru menjadi pihak yang paling terpinggirkan.
Jika ditelisik, model pembangunan yang diterapkan lebih berpihak kepada kepentingan korporasi dan elite kekuasaan dibandingkan kesejahteraan warga lokal. Janji pekerjaan dan peningkatan ekonomi sering kali berujung pada eksploitasi tenaga kerja, ketimpangan, dan kerusakan sosial. Masyarakat adat harus menghadapi intimidasi saat memperjuangkan tanah ulayat mereka, bahkan tidak jarang berujung kriminalisasi.
Pemerintah daerah dan pusat seharusnya menjadi penyeimbang antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan serta hak masyarakat adat. Namun dalam praktiknya, kebijakan yang dikeluarkan seringkali berat sebelah—mengizinkan perluasan konsesi tambang tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan suara masyarakat.
Halmahera bukan sekadar kawasan industri. Ia adalah rumah bagi ribuan jiwa yang memiliki sejarah, budaya, dan kehidupan yang tak ternilai harganya. Pulau ini bukan hanya sumber daya untuk dieksploitasi, tetapi warisan yang harus dijaga. Pembangunan semestinya berakar pada keadilan sosial dan kelestarian ekologis, bukan semata pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
Hutan Patani
Hari ini, Hutan Patani seperti gadis manis yang dilirik penuh nafsu oleh Jakarta dan elit global. Di mata mereka, Patani hanyalah lahan basah, sumber kekayaan baru yang siap dijarah. Mereka melihat hijau, tapi bukan sebagai simbol kehidupan melainkan sebagai tanda cuan yang menggoda.
Padahal, di sana terbentang bukan sekadar hutan. Itu adalah oikos, rumah bagi manusia, flora, fauna, dan segala jejak kehidupan yang tumbuh bersama waktu. Hutan Patani adalah jantung ekologi Maluku Utara. Ribuan manusia bergantung padanya, ratusan spesies endemik hidup dan berkembang biak di dalamnya.
Namun semua itu kini terancam, bukan oleh bencana alam, tapi oleh kerakusan manusia yang bersenjata kekuasaan dan investasi. Hutan yang seharusnya dijaga sebagai warisan peradaban justru dijadikan komoditas oleh mereka yang tak pernah hidup dari tanah ini.
Lebih dari sekadar hamparan vegetasi tropis, Hutan Patani adalah ruang hidup yang menyatu dengan budaya, spiritualitas, dan identitas masyarakat Patani. Menebang hutan ini bukan hanya merobohkan pepohonan itu sama saja dengan merobek jiwa dan sejarah satu bangsa kecil yang selama ini terpinggirkan.
Apakah kita akan diam ketika gadis manis ini dirampas paksa atas nama pembangunan? Atau kita berdiri lantang dan tegas untuk berkata: Cukup! Tak ada lagi satu jengkal pun tanah Patani yang boleh dijadikan korban kerakusan!
Patani berdiri di antara dua luka yang masih menganga: Weda dan Maba. Dua wilayah itu telah dikeruk, ditelanjangi, dan dikoyak oleh tambang. Dan apa hasilnya? Bukan kesejahteraan, tapi air mata. Bukan kemajuan, tapi konflik. Di sana, anak muda ditangkap, orang tua kehilangan tanah, dan masyarakat adat dipenjara hanya karena satu hal: mereka membela tanah leluhur mereka sendiri.
Kini, mata kapital mulai melirik Hutan Patani wilayah yang tersisa, yang masih hijau, yang masih bernapas. Padahal, hutan ini bukan sekadar hamparan pohon; ini adalah urat nadi hidup masyarakat. Bayangkan: 4.999 hektare hutan lindung, 1.324 hektare hutan produksi, 13.790 hektare lahan yang menopang kehidupan dipenuhi pala, cengkeh, dan kelapa tiga komoditas utama yang selama ini menjaga dapur rakyat tetap berasap.
Luas hutan yang tak seberapa itu ada yang ingin mengeksploitasinya, pemerintah harusnya melihat potensi yang ada disana, hutan Patani menyimpan kekayaan lebih dari sekedar emas, biji nikel dan batu bara.
Pala Patani menjadi Varietas paling unggul yang ditetapkan oleh kementerian Pertanian karena memiliki karakteristik morfologi. Tak hanya di sektor pertanian, potensi perikanan juga menjadi andalan. Teluk Midolafi menjadi spot dimana seribu jenis ikan bertelur, di sana selalu lahir kehidupan baru yang menjadi jawaban bagi siapapun.
Kenapa negara justru membiarkan kerakusan merambah ke sini? Mengapa suara rakyat selalu kalah oleh suara uang? Mengapa setiap kali tambang datang dengan janji “pembangunan dan kesejahteraan,” yang tertinggal justru air mata dan kerusakan?
Pemerintah kenapa tak melihat itu? kini beberapa izin telah keluar, PT BBH, PT SAS, hingga PT Duta Araco Investama. Mengapa tambang yang selalu menjadi solusi sebagai dalih pembangunan dan kesejahteraan. Padahal jelas tak pernah sedikitpun pembangunan dan kesejahteraan itu dialamtkan pada daerah apalagi wilayah lingkar tambang.
Cukuplah Weda dan Maba menjadi pelajaran. Jangan biarkan Patani menjadi luka berikutnya. Karena jika hutan ini tumbang, bukan hanya pepohonan yang mati tapi juga harapan, martabat, dan kehidupan sebuah masyarakat.
Maka wajar jika pertanyaan ini terus bergema: hutan patani untuk siapa? Untuk rakyat yang telah menjaga tanahnya selama berabad-abad, atau untuk segelintir pemilik modal dan pemegang izin usaha tambang?
Pemerintah juga harus sadar dan melindungi Patani dari segala jenis perusahan yang merusak alam, karena disanalah sang saka merah putih pertama kali dikibarkan sebelum bangsa ini masuk di pintu gerbang kemerdekaan.
Sudah saatnya kita meninjau ulang arah pembangunan di bangsa ini. Pembangunan yang sejati adalah yang melibatkan, mendengarkan, dan menyejahterakan masyarakat lokal, bukan yang menggusur dan meminggirkan mereka. (*)
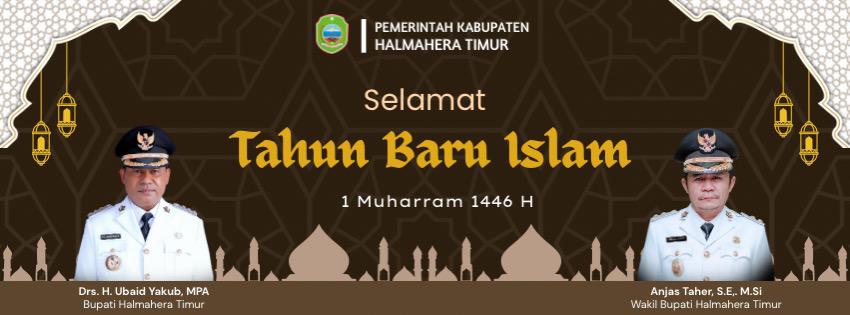

















Tinggalkan Balasan