Oleh: Iksan Nardi B
Advokat dan Pegiat Bantuan Hukum Cuma-cuma YLPAI Malut
_______
PENANGKAPAN beberapa warga Maba Sangaji oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara atas dasar penolakan aktivitas pertambangan di wilayah hutan adat mereka menyajikan suatu paradoks yang mencolok dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Di satu sisi, aparat penegak hukum menjalankan tugas berdasarkan aturan formal yang tertulis dalam perundang-undangan. Di sisi lain, tindakan tersebut justru bertabrakan dengan prinsip-prinsip keadilan substantif yang seharusnya menjadi roh dari penegakan hukum itu sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang bagaimana sistem hukum kita memosisikan masyarakat adat dan hak-hak kolektif mereka dalam konteks konflik sumber daya alam.
Tulisan ini akan menganalisis kasus penangkapan tersebut dari perspektif kriminologi kritis dan viktimologi, dengan mempertimbangkan kerangka hukum positif Indonesia serta instrumen perlindungan hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. Analisis ini penting untuk memahami dinamika kekuasaan yang beroperasi dalam kasus ini dan bagaimana sistem peradilan pidana sering kali berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan ekonomi-politik dominan daripada sebagai pelindung keadilan bagi kelompok marginal.
Analisis Kriminologis: Kriminalisasi Perlawanan Masyarakat Adat
Perspektif kriminologi kritis menawarkan lensa analisis yang tajam untuk memahami kasus penangkapan warga Maba Sangaji. Teori kriminologi kritis, sebagaimana dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Richard Quinney dan William Chambliss, memandang bahwa definisi dan penerapan hukum pidana tidak pernah netral, melainkan mencerminkan relasi kekuasaan yang timpang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pendefinisian perbuatan “kriminal” dan proses kriminalisasi tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi-politik yang mendominasi.
Tindakan penangkapan terhadap warga Maba Sangaji dapat dibaca sebagai suatu bentuk “kriminalisasi perlawanan” (criminalization of resistance), di mana instrumen hukum pidana digunakan untuk menekan gerakan sosial yang mengancam kepentingan ekonomi dominan. Dalam berbagai kasus penolakan terhadap aktivitas ekstraktif seperti pertambangan, kita seringkali melihat bagaimana pasal-pasal seperti “penghasutan”, “penghalangan aktivitas usaha”, atau bahkan “makar” digunakan untuk melegitimasi penangkapan para aktivis dan warga yang mempertahankan haknya.
Jika mengacu pada teori labeling (labeling theory) yang dikembangkan oleh Howard Becker, penangkapan warga Maba Sangaji tidak hanya merupakan tindakan koersif semata, tetapi juga merupakan proses pemberian stigma “kriminal” yang bertujuan untuk mendelegitimasi perlawanan mereka. Dengan membingkai aksi penolakan pertambangan sebagai tindakan kriminal, negara melakukan apa yang disebut Becker sebagai “moral enterprise“, yakni usaha sistematis untuk mendefinisikan perbuatan tertentu sebagai menyimpang dan memberi sanksi terhadapnya.
Di sisi lain, perspektif teori konflik (conflict theory) dalam kriminologi, seperti yang dikembangkan oleh George Vold dan Austin Turk, menawarkan pemahaman bahwa hukum pidana pada dasarnya adalah instrumen yang digunakan oleh kelompok dominan untuk melindungi kepentingan mereka. Dalam kasus Maba Sangaji, konflik kepentingan antara industri ekstraktif dan masyarakat adat diselesaikan melalui mekanisme kriminalisasi yang menguntungkan pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Terlebih lagi, institusi penegak hukum seperti kepolisian memiliki kecenderungan berpihak pada kepentingan modal besar karena pola relasi kuasa yang telah terbangun.
Perspektif Viktimologi: Masyarakat Adat Sebagai Korban Struktural
Pendekatan viktimologi kontemporer telah mengembangkan konsep “korban struktural” (structural victimization), di mana individu atau kelompok menjadi korban bukan hanya dari tindakan langsung pelaku kejahatan, melainkan dari struktur sosial, politik, dan ekonomi yang menindas. Dalam konteks ini, warga Maba Sangaji dapat dipandang sebagai korban dari sistem yang timpang, di mana hak-hak masyarakat adat secara sistematis disubordinasikan di bawah kepentingan kapital.
Benjamin Mendelsohn, salah satu pelopor viktimologi, mengembangkan tipologi korban yang menggambarkan spektrum dari korban yang sama sekali tidak bersalah hingga korban yang provokasi. Menariknya, dalam kasus-kasus konflik sumber daya alam seperti Maba Sangaji, seringkali terjadi “pembalikan narasi” di mana masyarakat adat yang sebenarnya adalah korban struktural justru dikonstruksikan sebagai “pelaku” atau “provokator” karena melakukan perlawanan. Pembalikan narasi ini merupakan strategi diskursif yang berfungsi untuk membenarkan tindakan represif negara terhadap gerakan perlawanan masyarakat.
Berdasarkan perspektif green victimology yang dikembangkan oleh Rob White, kerusakan lingkungan dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam merupakan bentuk viktimisasi yang sangat nyata namun sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Penangkapan warga Maba Sangaji justru merupakan bentuk “viktimisasi sekunder” (secondary victimization), di mana korban mengalami penderitaan tambahan akibat respons sistem peradilan pidana.
Hal ini sejalan dengan konsep “keadilan lingkungan” (environmental justice) yang menekankan bahwa distribusi kerusakan lingkungan dan akses terhadap sumber daya alam seringkali tidak merata dan mencerminkan ketimpangan struktural dalam masyarakat. Masyarakat adat seperti warga Maba Sangaji menanggung beban kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, sementara keuntungan ekonomi mengalir kepada elit politik dan ekonomi.
Analisis Yuridis: Kontradiksi dalam Sistem Hukum Indonesia
Secara yuridis, penangkapan warga Maba Sangaji yang mempertahankan hutan adat mereka menunjukkan kontradiksi mendasar dalam sistem hukum Indonesia. Di satu sisi, Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Di sisi lain, implementasi perlindungan tersebut seringkali terbentur pada kepentingan ekonomi-politik dan paradigma pembangunan yang ekstraktif.
Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, secara eksplisit menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Pengakuan konstitusional ini diperkuat dengan Pasal 28I ayat (3) yang menegaskan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan tonggak penting dalam pengakuan hak masyarakat adat atas hutan adat. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan bagian dari hutan hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Putusan ini secara fundamental mengubah paradigma penguasaan hutan di Indonesia dan memberikan landasan hukum yang kuat bagi klaim masyarakat adat atas wilayah hutannya.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2), mengakui kekhususan identitas masyarakat adat dan kewajiban negara untuk melindungi identitas tersebut. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakui kearifan lokal dan hak masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Meskipun memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk perlindungan hak masyarakat adat, implementasi di lapangan seringkali bertolak belakang dengan semangat peraturan tersebut. Salah satu penyebab utamanya adalah kontradiksi antar peraturan perundang-undangan, terutama antara undang-undang yang berorientasi pada perlindungan hak masyarakat adat dengan undang-undang sektoral yang mengatur investasi, pertambangan, dan kehutanan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, misalnya, memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah pusat dalam pengelolaan sektor pertambangan dan mengurangi peran pemerintah daerah. Hal ini berpotensi mengabaikan aspirasi masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat, dalam proses penerbitan izin pertambangan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) semakin memperkuat orientasi pro-investasi dengan menyederhanakan proses perizinan dan mengurangi persyaratan lingkungan. Meskipun UU Cipta Kerja masih mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, penerapan prinsip “kemudahan berusaha” dapat mengabaikan proses konsultasi dan persetujuan yang memadai dari masyarakat adat yang terdampak.
Dalam praktiknya, pengakuan terhadap masyarakat adat dan hutan adat masih terkendala oleh persyaratan formal yang memberatkan. Masyarakat adat diharuskan membuktikan keberadaan mereka melalui Peraturan Daerah, sementara proses pembuktian tersebut seringkali rumit, memakan waktu, dan melibatkan birokrasi yang panjang. Akibatnya, banyak masyarakat adat yang secara de facto ada dan memiliki hubungan historis dengan wilayahnya tidak mendapatkan pengakuan formal dari negara.
Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif
Menghadapi kontradiksi dalam sistem hukum dan kecenderungan pendekatan punitif dalam penanganan konflik sumber daya alam, paradigma keadilan restoratif (restorative justice) menawarkan alternatif yang lebih konstruktif. Pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana dikembangkan oleh Howard Zehr dan John Braithwaite, menekankan pemulihan hubungan yang rusak akibat konflik, ketimbang sekadar menghukum pelaku.
Dalam konteks konflik antara masyarakat Maba Sangaji dengan pihak pertambangan, pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan melalui beberapa langkah misalnya: fasilitasi dialog dan musyawarah antara masyarakat adat, perusahaan pertambangan, dan pemerintah dengan posisi yang setara bukan hierarkis; Mengakui penderitaan dan kerugian yang dialami oleh masyarakat adat akibat aktivitas pertambangan di wilayah mereka; Melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka; Memberikan ganti rugi yang adil atas kerugian yang dialami masyarakat adat, tidak hanya dalam bentuk material tetapi juga pemulihan hak-hak kolektif mereka; Mengubah struktur dan kebijakan yang selama ini melanggengkan ketidakadilan terhadap masyarakat adat.
Pendekatan keadilan restoratif tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik yang ada, tetapi juga mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan melalui transformasi relasi kekuasaan yang lebih setara. Dalam konteks ini, pembebasan warga Maba Sangaji yang ditangkap dan pelibatan mereka dalam dialog yang bermartabat merupakan langkah awal yang penting dalam proses keadilan restoratif.
Kesimpulan
Penangkapan warga Maba Sangaji yang menolak aktivitas pertambangan di wilayah hutan adat mereka merupakan refleksi dari paradigma penegakan hukum yang belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip keadilan substantif dan pluralisme hukum. Melalui lensa kriminologi kritis dan viktimologi, kita dapat memahami bahwa tindakan penangkapan tersebut tidak hanya merupakan persoalan teknis-yuridis, melainkan juga mencerminkan relasi kekuasaan dan struktur ekonomi-politik yang mendominasi.
Kontradiksi dalam sistem hukum Indonesia, di mana pengakuan terhadap hak masyarakat adat berdampingan dengan kebijakan yang berorientasi pada ekstraksi sumber daya alam, menciptakan ruang bagi terjadinya kriminalisasi terhadap perlawanan masyarakat adat. Dalam konteks ini, pendekatan keadilan restoratif dan reformasi sistem peradilan pidana menawarkan alternatif yang lebih konstruktif untuk menyelesaikan konflik dan mencegah viktimisasi lebih lanjut terhadap masyarakat adat.
Pada akhirnya, kasus Maba Sangaji mengingatkan kita akan pentingnya membangun sistem hukum yang tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif bagi seluruh komponen masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang secara historis terpinggirkan seperti masyarakat adat. Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alam mereka bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga prasyarat bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia. (*)



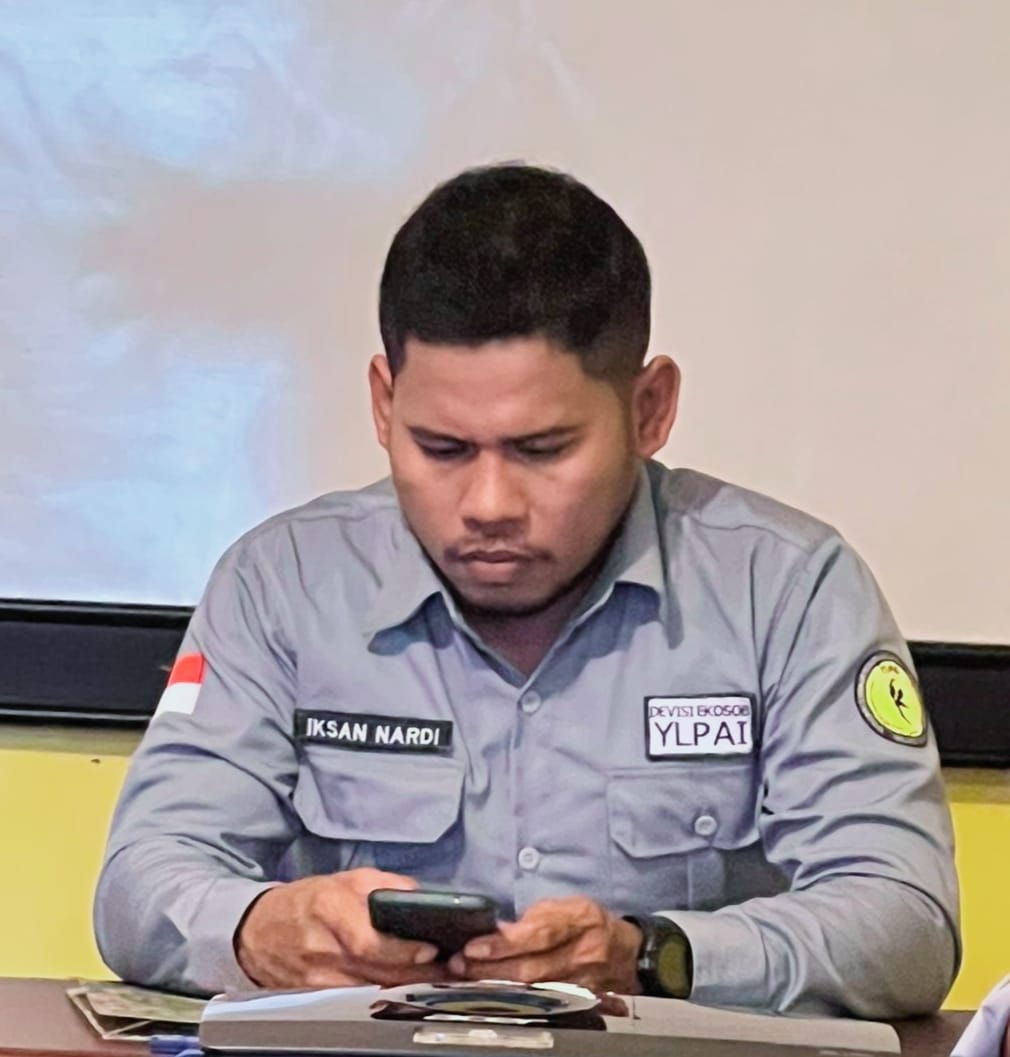
















Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.