Oleh: A. Malik Ibrahim
_______
DI era digital ini, sepertinya banyak orang mulai skeptis dengan buku. Seolah buku hanya kumpulan kertas penuh kata-kata hampa. Buku hanya benda mati. Kertas yang berisikan puluhan ribu kata dan sesekali gambar pelengkap.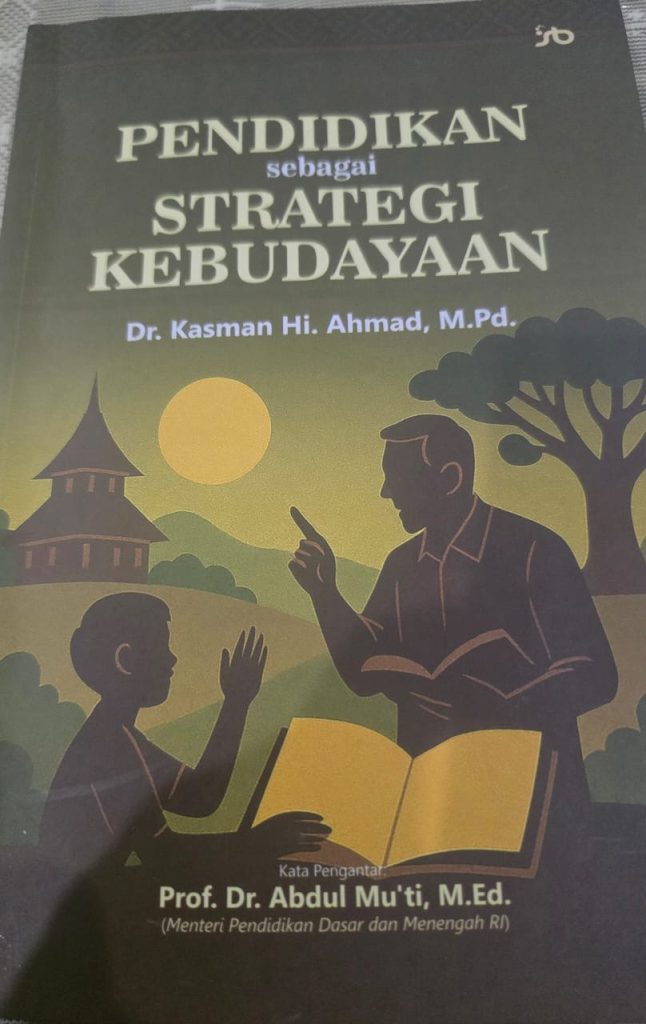
Namun, dalam hal keutamaan, kita belajar dan berutang budi pada buku. Buku– adalah penanda sejarah kesadaran hati yang “ditulis dan dihidupkan” seorang penulis. Sebab apa yang ditulis, bukanlah benda, tetapi proses dari sebuah penelaahan kritis. Dan pengetahuan adalah kebajikan, mata air yang tak kering. Ilmu yang tak bakal habis ditimba.
Kedalaman sebuah buku dengan segala aspeknya, ia ditulis dengan hati. Rasulullah saw dalam hadis qudsi: “Aku bangun di dalam rongga manusia sebuah istana, di dalam istana ada dada/shadr, di dalam shadr ada hati/qalb, di dalam qalb ada hati/fuad, dalam fuad ada cinta/syagaf, di dalam syagaf ada hati nurani/lub, di dalam lub ada rahasia/sir, dan dalam sir ada Aku/Allah SWT” (Istilah Tasawwuf, Suparlan, hal.81.)
Menarik, membaca buku ke-9 karya Dr. Kasman Hi. Ahmad ini – lebih dari sekadar sumber refleksi mengenai Pangaji, karena keprihatinannya pada hilangnya kearifan lokal. Sebagai aktivis, akademisi dan hari ini seorang birokrat (Wakil Bupati Halut) – ia adalah sosok yang dibesarkan dari tradisi filsafat ilmu pengetahuan.
***
Salah satu pertimbangan Dr. Kasman menulis buku ini adalah keinginannya untuk membangun analisis kelembagaan modern Pangaji (dalam pengertian sosiologis) dengan perspektif “Pendidikan sebagai Strategi Kebudayaan” yang jadi basis epistemologinya.
Dalam pandangan Dr. Kasman, Pengaji bukan hanya praktik pendidikan keagamaan, tetapi juga strategi kebudayaan dalam membangun sumber daya manusia berkarakter dan beridentitas. Dengan pendekatan kultural dan reflektif, pengaji terbukti memainkan peran penting dalam membentuk etos kerja, nilai-nilai kolektif, dan spiritualitas komunitas. Keberlanjutan dan relevansi pengaji di era modern sangat tergantung pembangunan pada SDM yang inklusif, kontekstual , dan berbasis nilai lokal. (lihat kesimpulan, hal. 129).
Diskursus tentang Pangaji – sebuah entitas dimaknai sebagai satuan yang berwujud – maujud. Sesuatu yang unik dan memiliki identitas berbeda dengan institusi sosial lainnya. Apa yang disebut entitas adalah kesatuan yang berdiri sendiri; bisa berupa individu (personal), organisasi atau ekosistem yang memiliki tanggung jawab etis pada masyarakat.
“Dalam karya ini, tulis Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed, “Dr. Kasman mencoba menempatkan pendidikan, dengan memberi perhatian khusus pada bagaimana budaya lokal, yang disebut Pangaji, dapat dijadikan fondasi dan sumber inspirasi dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah membangun kesadaran bahwa pendidikan yang berpihak pada kebudayaan lokal bukanlah suatu romantisme, melainkan strategi penting untuk membangun masyarakat yang berdaulat secara kultural”, (lihat Pengantar, hal.xiii).
Diperlukan internalisasi nilai Pangaji, karena menurutnya, “Pangaji bukan sekedar pengajaran hafalan ayat suci, melainkan sebuah praktik kultural yang menginternalisasi nilai-nilai moral, sosial, dan spiritualitas dalam kehidupan masyarakat (hal. 125).
***
Dalam konteks ini bagi saya, Pangaji sebagai entitas perubahan berarti diperlukan strategi untuk menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia melalui peran sertanya dalam pembangunan. Karena bagaimanapun, kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan keterpencilan, buta aksara, gizi buruk, stunting, pendidikan rendah, dan tidak adanya sumber daya yang memadai, tetapi juga kebiasaan dan mindset. Mindset masyarakat, dan juga mindset para pejabatnya. Semua saling berkaitan.
Pendekatan pendidikan haruslah didefinisikan berbeda. Sesuai falsafah, tujuan, dan sosiokultural, di mana Pangaji itu berperan. John Dewey merumuskan education is all one growing, it has no end beyond it self. Pendidikan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penumbuhan, dan pendidikan tidak punya tujuan akhir di balik dirinya.
Gaya dan teknik implementasi kepemimpinan Pangaji mulai dari gaya otokritik, paternalistik dan kharismatik sesungguhnya masih bersifat konvensional (hal. 71 -75). Sangat fleksibel dan masih tergantung pada kapasitas dan kapabilitas Joguru. “Oleh karena itu, program pembangunan SDM yang mengabaikan potensi kebudayaan lokal seperti Pangaji akan kehilangan dimensi penting dari pembangunan manusia yang utuh” ,(hal.128).
Sementara, pada banyak isu publik masa kini, sedang tumbuh suatu jenis kepemimpinan sosial yang berakar pada kesadaran tentang satu kemanusiaan, satu planet, satu keadilan dan satu perdamaian. Artinya, kepemimpinan bukan lagi dipahami dalam arti kompetisi otoritas, melainkan sebagai kolaborasi berbasis humanitas.
Buku ini mengungkap dimensi sejarah, sosial dan budaya Pangaji, serta bagaimana adaptasinya di tengah perubahan zaman. Tentu relevan dengan kalimat Charles Darwin, “Survival of the fittest”. Fittest artinya mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Jadi, kunci survive itu bukan siapa yang paling kuat, paling kaya atau paling cerdas, tetapi siapa yang paling adaptif. Lalu, apa konteksnya setelah membaca buku ini? Jawabannya adalah : inovasi sosial. Semua harus melalui pendidikan dan kebudayaan agar kita tetap survive di tengah perubahan lingkungan strategis. Selamat membaca. (*)
RESENSI BUKU:
Judul: Pendidikan sebagai Strategi Kebudayaan
(Yogyakarta, Penerbit Samudra Biru, 2025), xx+146 halaman.


















Tinggalkan Balasan