Oleh: Arafik A Rahman (Bung Opickh)
_________
“I shall return (aku akan kembali)”
_Jenderal Douglas MacArthur_
Kembali untuk memenangkan perang Pasifik 1942-1945. Sebuah kalimat simpel namun sarat makna dan peringatan dalam militer.
PULAU Morotai tak pernah benar-benar tidur. Dalam senyapnya laut dan panasnya mentari yang datang dari bibir Pasifik, menancap di antara pepohonan, sungai, bukit dan batu karang, tersimpan rekam jejak yang tak ternilai. Dari zaman nomaden, cerita tentang bajak laut di timur Indonesia, pertempuran sengit di masa Perang Pasifik hingga medan politik lokal.
Morotai menjadi tanah yang melahirkan bukan hanya sejarah, melainkan juga manusia-manusia dengan mental, daya tahan dan taktik setara jenderal. Tulisan ini dengan sengaja menelusuri benih-benih kepemimpinan yang tumbuh dari tanah keras ini, dengan meminjam lensa tiga pemikir dunia: Clausewitz, Foucault dan Gramsci.
Mereka datang bukan untuk menepi, tetapi untuk menguasai. Laksamana Yamamoto menginjakkan sepatu perangnya di pasir timur Morotai demi membentengi ambisi Jepang Raya. Di sisi lain, Jenderal MacArthur bersama Krueger dan Phillips membalas dengan keperkasaan armada Sekutu. Tanah ini yang dahulu hanya dikenal nelayan dan petani kelapa berubah menjadi panggung global, tempat di mana strategi dan darah saling berebut tempat.
“Old soldiers never die, they just fade away.”
Prajurit tua tak pernah mati, mereka hanya menghilang perlahan. Kutipan yang disampaikan MacArthur saat pidato perpisahan jelang masa pensiunnya di Kongres AS pada 1951.
Namun sejarah bukan sekadar tentang siapa menang dan siapa kalah. Morotai menyerap semuanya ke dalam tanahnya; suara ledakan, strategi di balik radio di desa Juanga, lapangan pantai Wawama dan Pulau Zum-Zum keputusan-keputusan besar tercipta yang menentukan arah perdamaian dunia. Di tengah reruntuhan dan pangkalan-pangkalan tua, lahir pula kepemimpinan dari rahim lokal.
Pemimpin-pemimpin Morotai, baik yang menjabat sebagai bupati, wakil, maupun anggota dewan, seakan hanya mampu bertahan jika mereka punya mental jenderal: kuat, tangguh dan penuh siasat. Kepemimpinan di Morotai tumbuh bukan dari organisasi, workshop, seminar atau pelatihan birokrasi. Ia tumbuh dari pengalaman hidup yang penuh dengan tekanan, tantangan dan ketidakpastian.
Dalam keseharian yang penuh dengan perang, telah mengenal teknologi barat, listrik, jalan sekutu, akses satelit (radio), perusahaan BBM, minuman bermerek, jus Lemon dan peralatan perang canggih lainnya. Orang Morotai sudah melihat itu di masa sebelum kemerdekaan. Disisi lain, ada juga kehidupan yang keras pascakemerdekaan, sejak masa Orde Baru semua fasilitas dan peninggalan sejarah sengaja dihilangkan, sulit mendapatkan pendidikan, kesehatan dan pelayanan administrasi yang layak.
Mereka berperang melawan isolasi, kebijakan tak sampai, pusat yang sering lupa dan iklim alam yang tak selalu bersahabat. Dalam pertarungan itu, dibutuhkan insting dan logika kepemimpinan yang sebanding dengan medan perang. Tetapi Morotai tak hanya melahirkan jenderal dalam pengertian militer. Ia juga menanamkan watak kepemimpinan dalam tubuh masyarakatnya: kesabaran yang ulet, keberanian untuk berbeda, dan ketangguhan menghadapi tekanan.
Jika kekuasaan bisa bersembunyi di balik hal-hal biasa, seperti yang pernah dikatakan Michel Foucault, bahwa kuasa tak hanya tinggal di istana, tetapi menyebar lewat kebiasaan, norma dan disiplin yang mengendap dalam tubuh sosial. Maka Morotai adalah contoh hidup dari kuasa yang diserap oleh rakyatnya sendiri.
Anak-anak mudanya pemberani, kritis, ada juga yang pragmatis, kocaknisasi ibarat peran yang menampilkan seorang intelijen FBI dan CIA yang lihai berkamuflase, suka berdebat dan percaya diri untuk tampil bahkan mencalonkan diri sebagai pemimpin. Perempuan-perempuannya bicara setara dalam forum adat, region dan internasional (berhadapan dengan tamu-tamu mancanegara).
Bahkan di ruang-ruang nongkrong, diskusi tentang tanah, kebijakan dan pendidikan lebih sering terdengar daripada sekadar candaan kosong. Yang lebih menarik, nilai-nilai ini tidak dipaksakan. Mereka tumbuh secara sukarela, menjadi semacam hegemoni sosial. Antonio Gramsci pernah berkata bahwa hegemoni sejati terjadi ketika masyarakat secara sadar menerima nilai-nilai tertentu sebagai “wajar” dan “benar”, bukan karena dipaksa, tetapi karena diyakini.
Di Morotai, nilai keberanian dan daya tahan sudah menjadi bagian dari identitas kolektif. Anak-anak tumbuh dengan cerita-cerita kepahlawanan kakeknya di hutan. Remaja percaya bahwa lebih baik berkata jujur meski kehilangan jabatan, daripada berkompromi dengan kebodohan. Bahkan secara historis, Morotai seperti memiliki semacam “takdir geopolitik” untuk mencetak jenderal.
Beberapa perwira tinggi Indonesia yang pernah ditugaskan atau menginjak di Morotai: Ir. Soekarno, Megawati, Soekarnoputri Susilo Bambang Yudhoyono, Faisal Tanjung, Irfan Tombokan dan lainnya naik menjadi orang-orang hebat bahkan jenderal dan panglima. Bagi mereka, bertugas di pulau ini bukan sekadar penempatan, melainkan ujian.
Sebab medan yang sunyi kadang lebih berat daripada medan yang gaduh. Di Morotai, seorang pemimpin belajar bagaimana sunyi bisa menjadi senjata dan keteguhan lebih penting dari gembar-gembor. Kini, ketika dunia tak lagi terbelah oleh perang dingin dan peluru, Morotai tetap menyimpan energi strategisnya bukan lagi untuk invasi militer, tapi untuk perjuangan martabat dan pembangunan.
Mereka yang memimpin Morotai tanpa mental jenderal biasanya cepat menyerah. Mereka yang tumbuh di tanah ini, dari petani, pemuda, hingga politisi mewarisi watak sejarah yang dalam. Morotai bukan tanah biasa. Ia adalah tanah yang mengajari manusia untuk bersiasat tanpa kehilangan integritas, untuk bertahan tanpa kehilangan semangat.
Di tanah ini, sejarah masih berbicara dalam cara orang berjalan, bekerja, dan bermimpi. Maka tak keliru bila Bung Opickh menyebutnya: Morotai, Tanah Para Jenderal. (*)
Daftar Referensi:
- Clausewitz, Carl von. On War. Princeton University Press, 1984
- Foucault, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Vintage Books, 1995
- Gramsci, Antonio. Selections from the Prison Notebooks. International Publishers, 1971
- Opickh, Bung. Perang Pasifik, Pemekaran dan Pembangunan. Morotai: Ruang Aksara, 2022
- Dokumentasi Morotai dalam Arsip Perang Dunia II dan wawancara dengan tokoh lokal.


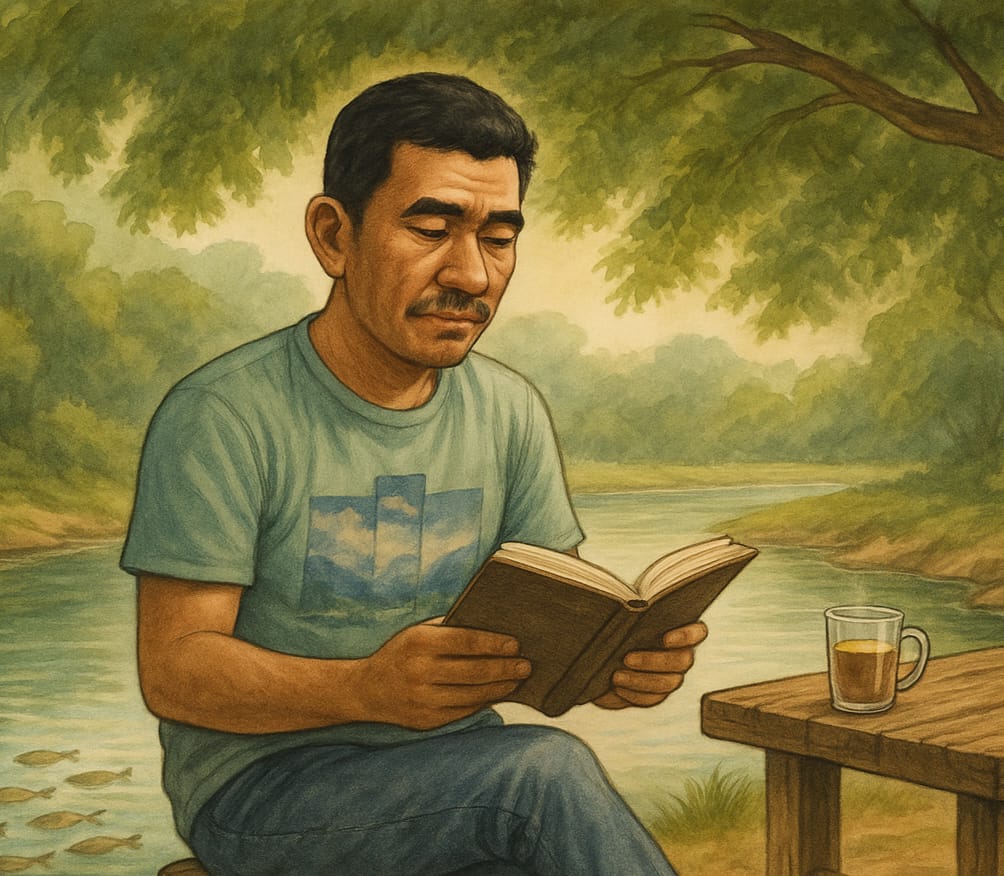
















Tinggalkan Balasan