Letak Kepulauan Widi yang berbatasan dengan perairan Papua Barat membuat kawasan ini minim pengawasan otoritas, baik sipil maupun militer. Apalagi, tak ada pula papan keterangan yang menerangkan Kepulauan Widi merupakan kawasan konservasi.
“Kalau nelayan yang rutin mencari ikan di Widi tidak ada yang berani pakai bom atau potas. Itu nelayan luar,” kata Podo, nelayan asal Desa Gane Luar.
Selain ancaman destructive fishing, sebagian nelayan Kepulauan Widi juga bergantung pada perahu fiber milik orang lain. Mereka terpaksa harus menyewa perahu milik orang lain dengan nilai Rp 1,5 juta per 10 hari.


“Nelayan tanpa perahu ibarat burung tanpa sayap,” ucap Muhammad Amin.
Amin punya perahu kayu. Tapi sudah tak laik dipakai, apalagi untuk mengangkut banyaknya hasil tangkapan ikan mereka.
Alhasil, biaya sewa perahu membuat pendapatan mereka ikut tergerus. Sama halnya dengan ketiadaan Kartu Nelayan yang membuat mereka tak bisa membeli BBM subsidi.
“Kalau nelayan di Halteng ada Kartu Nelayan, tapi kita di Halsel belum dapat,” sambung Johardin.
Lepas dari itu semua, Kepulauan Widi adalah anugerah bagi para nelayan. Di sini dapat ditemui nelayan dari berbagai daerah dan suku. Bajo, Buton, Bugis, Tobelo, Gane, hingga Makian-Kayoa ada di pulau-pulau kecil ini.

Mereka membentuk kelompok-kelompok nelayan (tanpa ada sekat suku) untuk menangkap, mengolah, dan menjual ikan. Ada yang menjualnya hingga ke Makassar, Sulawesi Selatan.
Johardin, misalnya, meninggalkan Menui untuk mengikuti bibi-bibinya yang menikah di Pulau Dowora, Halsel. Namun ia berjodoh dengan warga Desa Foya dan kini hidup bersama empat anak mereka di Kotalow.











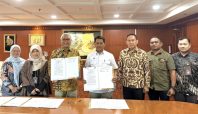


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.